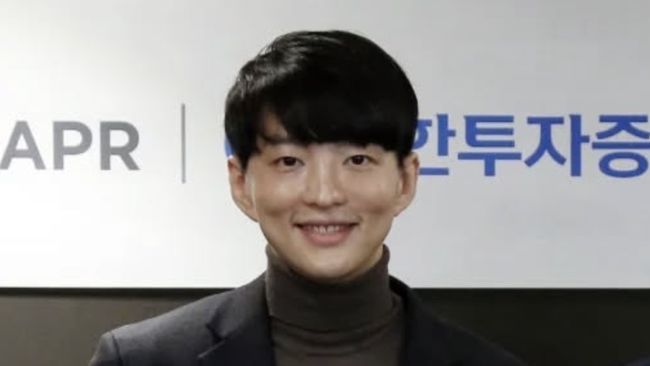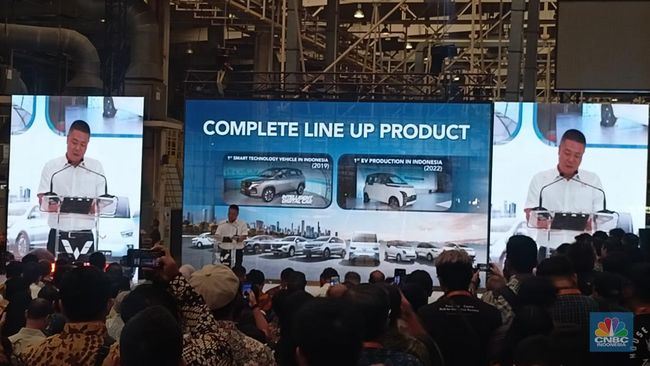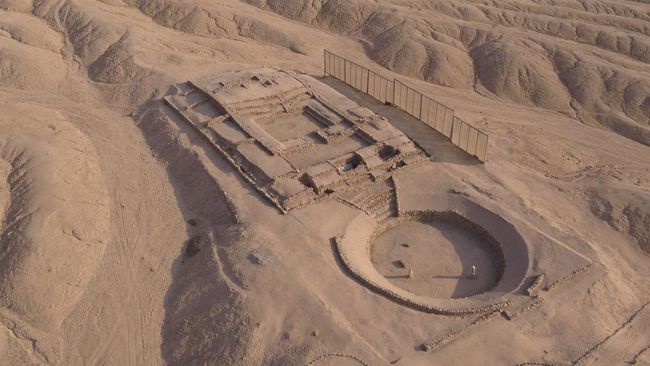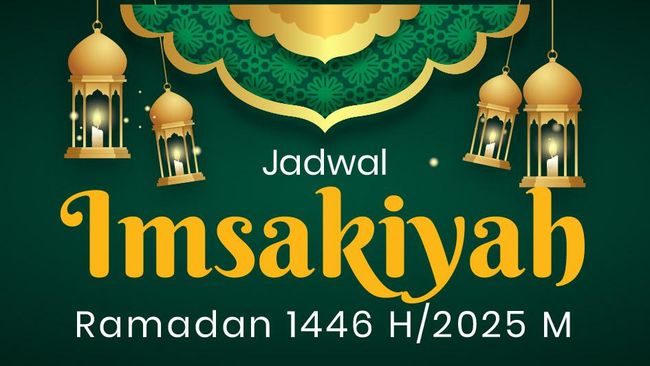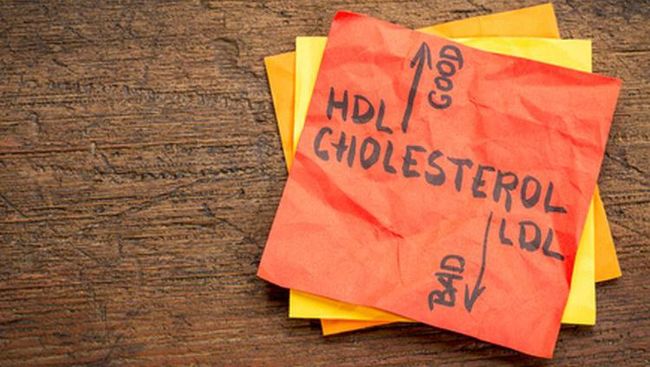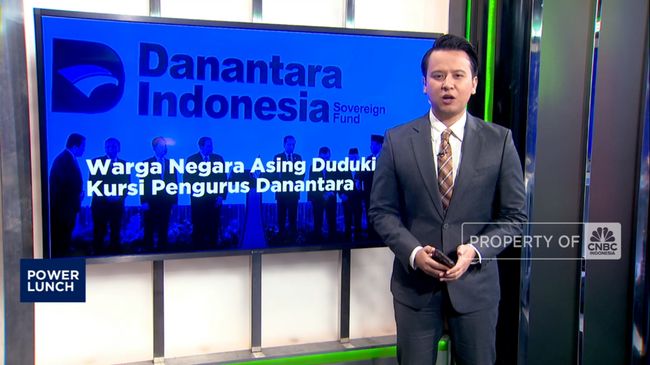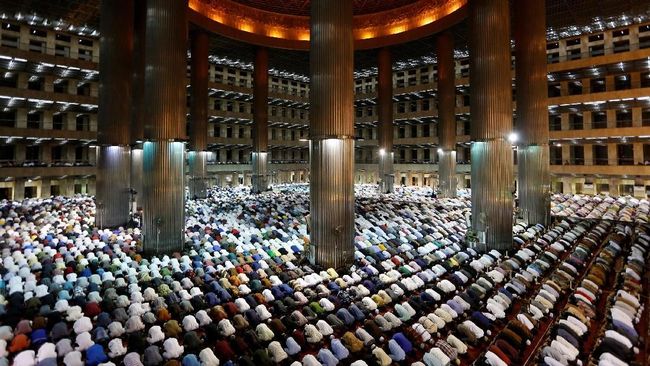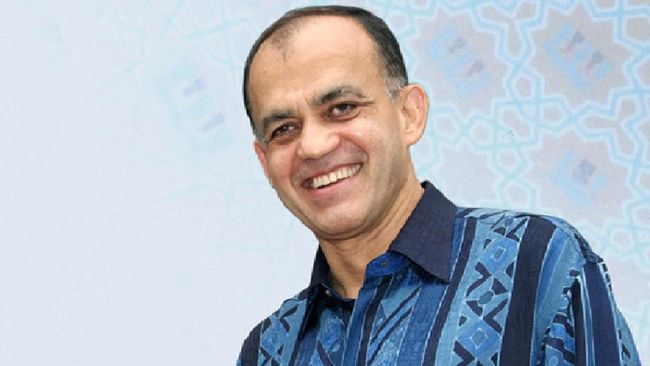Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Mungkin tak terlalu penting benar, hari ini manusia hidup 'dalam budaya algoritma' atau hidup 'dengan budaya algoritma'. Benar-benar tak penting pula untuk menelusuri, Shilla yang demam mengonsumsi matcha atau Adam yang intensif berolahraga Padel, dan Nadya yang keras berlatih joget Velocity lantaran terpengaruh media sosial yang dikonsumsinya. Atau kegemaran itu, muncul sebagai kecocokan perilaku sesuai kehendak dirinya. Keduanya adalah realitas yang dipraktikkan, dan tak sepenuhnya disadari.
Namun yang membedakannya: pada kemungkinan kedua, peran subyek sebagai makhluk yang berkehendak bebas -mengandalkan pertimbangan rasional, mengendalikan dorongan hasrat, berikut menyeleksi aneka alternatifnya-- masih seutuhnya. Unsur kehendak bebas, bersama faktor eksogen teknologis: sistem pengolah data statistik-komputasional pembentuk algoritma, menimbang hadirnya kebiasaan.
Kebiasaan yang menjadi perilaku bersama, ditularkan lewat media sosial. Pengulangannya, menumbuhkan minat khalayak. Sehingga dipersepsi sebagai budaya. Sedangkan pada kemungkinan pertama, semata-mata faktor eksogen teknologislah yang membentuk perilaku khalayak. Perilaku dengan pengikut banyak, terpromosi lewat media sosial. Juga menghasilkan praktik yang seolah-olah diminati khalayak, lantas dipersepsi sebagai budaya.
Walaupun unsur pertimbangan subyek tak sepenuhnya dapat ditiadakan, dominasi pengendalian oleh faktor eksogen menghilangkan kehendak bebas subyek. Mengeliminasi peran subyek, sekedar sebagai konsumen kepentingan ekonomi maupun politik. Erik van Dorp, 2024, dalam "Algorithm Steps: How to Build Your Own Algorithm", menguraikan: algoritma merupakan rangkaian instruksi yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas.
Mulai tugas analisis data, hingga pengambilan keputusan. Bagian terpenting algoritma adalah terungkapnya pola tersembunyi dari timbunan data yang dianalisis. Pola itu menampilkan perilaku sejati, terungkap oleh pemetaannya yang sistematis. Dengannya, dapat diprediksi perilaku selanjutnya. Sehingga algoritma dapat difungsikan sebagai sistem penunjang pengambilan keputusan, decision support system.
Pengertian algoritma oleh Dorp ini, senada dengan pernyataan Nick Seaver, 2017, dalam "Algorithms as Culture: Some Tactics for The Ethnography of Algorithmic Systems". Seaver menyebut, algoritma merupakan inti dari ilmu komputer yang memiliki definisi lugas.
Dalam pandangan para humanis, disebut sebagai kasus rasionalisasi yang mengandalkan kuantifikasi dan berbasis pada prosedur logika. Lugas yang dimaksud Seaver, tampaknya mengacu pada kuantifikasi bermakna tunggal, dari fenomena yang kaya nuansa kualitatif.
Hari ini, algoritma mendasari seluruh ciri kerja perangkat berbasis teknologi informasi. Pengurai kemacetan lalu lintas --yang mengandalkan data jumlah kendaraan, rata-rata kecepatan dan ukuran kendaraan, yang dibandingkan dengan luas penampang jalan raya-mendasarkan kerjanya pada algoritma. Caranya, dengan mengatur nyala hijau-kuning-merah lampu lalu lintas di persimpangan jalan raya, untuk menghindarkan penumpukan kendaraan yang memacetkan jalan raya.
Algoritma mendistribusikan pembagian waktu di setiap ruas persimpangan, menurut kepadatannya. Tak ada lagi alokasi waktu yang sama, untuk kepadatan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan HRD yang menyeleksi tenaga kerja yang hendak direkrutnya. Seleksi akan menjadi pekerjaan kompleks --butuh waktu yang banyak dan rentan mengalami kesalahan-- ketika data ribuan pelamar dibaca satu per satu mengandalkan panca indera.
Algoritma --berdasar data-data penting pembentuk kinerja: pengalaman kerja, umur, riwayat penyakit, tingkat pendidikan, maupun lembaga tempat menempuh pendidikan terakhir-- dibangun. Campuran data alfabetis maupun numeris, diubah sebagai algoritma yang lugas. Seluruhnya mengandalkan hasil kerja statistik-komputasional, yang meringkas proses seleksi sebagai skor kuantitatif. Peringkat pelamar, berapa pun jumlahnya dapat disusun memudahkan pemilihan.
Penerapan algoritma di berbagai bidang lain --termasuk pengumpan video Youtube, film rekomendasi Netflix untuk tontonan berikutnya, teman Instagram yang disarankan, genre musik yang layak dinikmati di Spotify. Juga persetujuan dan jumlah kredit yang diberikan bank, hingga prediksi pelaku berikut tempat kejahatan-- seluruhnya mengandalkan algoritma.
Keluasan penggunaan algoritma, tak menghindarkannya mengatur bahkan membentuk perilaku khalayak. Ini kemudian diikuti dengan pembentukan budaya. Kehidupan yang didominasi oleh pengaturan algoritma, disebut algokrasi. Algokrasi jadi realitas hari ini.
Seluruh uraian di atas, juga sesuai pendapat Nicoletta Boldrini, 2017, dalam "Algocracy and Surveillance Capitalism: We live in a World Governed by Algorithms". Boldrini kurang lebih menyebut: hal yang dialami manusia di jejaring sosial, merupakan hasil kerja algoritma. Ini terbentuk sebagai hasil seleksi, yang disusun menjadi model matematika dan diterjemahkan sebagai kode komputer.
Cara beroperasi algoritma, selayaknya instrumen penentu namun tak tampak mata. Bahkan tak sepenuhnya disadari. Perannya dapat membantu dan meluaskan kehidupan. Dominasi algoritma ini, berkembang mewarnai era yang berlangsung: era algoritma. Ini termasuk dunia yang diatur oleh artificial intelligence (AI). Yang seluruhnya berimplikasi pada digenggamnya kekuasaan sosial, ekonomi, maupun politik, di tangan yang mampu memodelkan dan mengendalikan algoritma.
Pada penerapan social credit system (SCS) untuk menegakkan keamanan bagi warga negara China --yang jumlahnya tak kurang dari 1,4 miliar orang-- algoritma berperan memuaskan. Pemetaan warga negara, dengan skor algoritma yang mengkategorikan kemungkinan dilakukannya tindakan jahat.
Skor tinggi untuk perilaku baik, dan skor rendah untuk sebaliknya. Agar perilaku 'tak mengancam keamanan' bertahan, skor diikuti pemberian insentif. Bisa berupa kemudahan layanan sosial: pemberian kredit perbankan maupun penerbitan visa yang cepat untuk perjalanan ke luar negeri.
Dan yang sebaliknya dilakukan pada warga negara yang berpeluang mengacau. Ini berupa pembatasan maupun pengawalan, saat memasuki fasilitas publik. SCS untuk mencegah kejahatan, juga mendorong warga negara melakukan perbuatan baik, yang dapat menaikkan skornya.
Seluruhnya kemudian dipahami: implikasi kehidupan yang didominasi algoritma, adalah minimalnya kesertaan emosi yang bersifat kualitatif. Pilihan pada buku bacaan misalnya, didasarkan jumlah bintang yang disematkan oleh pembaca terdahulunya. Pertimbangannya kuantitatif.
Kalaupun terdapat testimonial yang bersifat naratif, dikuantifikasi berdasarkan kata-kata kuncinya. Seluruhnya memudahkan sistem penjualan oleh lapaknya, mengandalkan kelugasan algoritma. Tak ada pertimbangan emosional: memilih buku karena kagum pada konsistensi penulis. Juga mempertimbangkan kegigihannya menyelesaikan karya di tengah perjuangan mengasuh bayinya.
Demikian juga saat memilih warung makanan, tak pernah karena pertimbangan: pemiliknya adalah korban PHK. Posisi semula pemilik warung --sebagai petinggi sebuah perusahaan-- namun akibat ekonomi yang buruk, memaksa perusahaan tempatnya bekerja melakukan PHK.
Tak menyerah melanjutkan hidup sekaligus menafkahi keluarganya, mantan petinggi perusahaan gigih menjalani hidup dari awal. Membuka warung makanan, dengan mengandalkan kesenangan memasak di waktu senggang saat bekerja dulu.
Ini adalah narasi kehidupan, yang dapat memengaruhi penilaian terhadap makanan yang dikonsumsinya. Bahkan inspirasi bagi konsumen, dalam menghadapi hidup yang tak selalu dapat diprediksi. Hanya mengandalkan pemeringkatan kuantitatif, didapati dasar pertimbangan yang kering, miskin nuansa, dan pengalaman kolektif terbatas bersama konsumen lainnya. Bahkan dapat mengubahnya jadi konsumen yang seragam.
Untuk rekrutmen tenaga kerja, mana yang lebih menguntungkan: perusahaan memperoleh karyawan --yang untuk melamar calon tempat bekerjanya, dilakukannya dengan lebih dulu menelusuri portofolio perusahaan, menyesuaikan kemampuan dirinya dengan budaya perusahaan dan menjawab pertanyaan wawancara dengan menyiapkan lebih dulu pewawancara maupun pertanyaan yang mungkin diberikan?
Atau calon tenaga kerja yang terpetakan algoritmanya, berdasar pengalaman kerja, riwayat kesehatan, pendidikan terakhir dan lembaga tempat menempuh pendidikan terakhirnya? Memang algoritma memudahkan. Juga ada pertanggungjawaban kuantifikasinya. Namun yang hilang, ketika semua nuansa kualitatif dipangkas. Agar tercapai ukuran obyektifnya.
Walaupun tak hendak mengkontraskan mana yang lebih baik diterapkan: algoritma kuantitatif atau kespontanan kualitatif? Namun ada masalah yang muncul dengan budaya yang penerapannya semata-mata algoritmis. Kerentanan akibat bias maupun manipulasi algoritma.
Algoritma yang mengandalkan pengolahan dan analisisnya pada teknologi yang diinisiasi manusia, tak pernah lepas dari kelemahan inheren manusia. Ini melahirkan bias. Soal pandangan dunia yang lebih bercorak laki-laki --alih-alih setara menghadirkan pandangan perempuan-terepresentasi sebagai algoritma yang mewariskan corak timpang itu.
Biasnya peran gender. Sedangkan manipulasi algoritma, selalu diupayakan oleh pihak yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik tanpa landasan etika yang kuat. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan.
Yang jelas dunia yang penuh nuansa ini, direduksi. Seluruhnya agar dapat dikuantifikasi sebagai algoritma. Selayaknya kacamata yang dibatasi untuk dapat melihat seluruh keutuhan semesta, melihat kealamiahan dalam realitas algoritma adalah menikmati dunia yang tak hadir utuh. Ketakutuhan yang disusun oleh mereka yang punya kepentingan. Apa menariknya dunia yang tak hadir utuh itu?
(miq/miq)